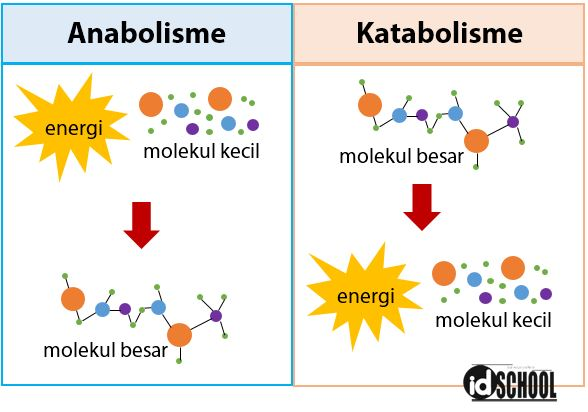Klasifikasi
ikan patin siam menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut :
Kingdom :
Animalia
Filum :
Chordata
Kelas :
Pisces
Famili :
Pangasidae
Genus :
Pangasius
Spesies
: Pangasius hypophthalmus
Ikan
patin siam mempunyai bentuk tubuh memanjang berwarna putih perak dengan
punggung berwarna kebiruan. Ikan patin tidak memiliki sisik, sirip punggung
memiliki sebuah jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang besar dan
bergaris dibelakangnya, sedangkan jari-jari lunak pada sirip punggungnya
terdapat 6-7 buah (Kordi, 2005). Permukaan punggung ikan patin terdapat sirip
yang ukurannya kecil. Sirip dubur memiliki 30-33 jari-jari lunak, sirip perut
ikan patin terdapat 6 jari-jari lunak, sirip dada terdapat satu jari-jari keras
dan 12-13 jari-jari lunak, dan sirip ekor berbentuk simetris (Ghufron, 2005). Tubuh
ikan ini memiliki panjang hingga mencapai 120 cm, bentuk kepala yang relatif
kecil, mulut terletak di ujung kepala bagian bawah, pada kedua sudut mulutnya
terdapat dua pasang kumis yang berfungsi sebagai alat peraba yang merupakan
ciri khas ikan golongan catfish, dan
memiliki sirip ekor berbentuk cagak dan simetris (Djariah, 2001). Morfologi
ikan patin dapat dilihat pada gambar.

Gambar
Morfologi Ikan Patin
(Sumber :
Standart Nasional Indonesia, 2000)
Keterangan :
a. Mulut e. Sirip punggung (dorsal fin)
b. Mata f. Sirip perut (ventral fin)
c. Tutup
insang (operculum) g.
Sirip anus (anal fin)
d. Sirip dada (pectoral
fin) h. Sirip ekor (caudal fin)
❤ Habitat dan Penyebaran
Ikan patin merupakan ikan air tawar yang
hidup di sungai dan muara sungai serta danau yang mampu bertahan pada lingkungan
perairan yang jelek, misalnya kekurangan oksigen. Ikan patin dikenal sebagai
hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari dan sebagai hewan dasar
yang suka bersembunyi di liang-liang tepi sungai (Ghufron, 2005). Suhu air yang
optimum untuk selera makan ikan antara 22-29˚C, pada suhu tersebut ikan akan
makan dengan rakus, hal ini terjadi pada waktu pagi hari dan sore hari. Oleh
karena itu pemberian makan yang paling baik adalah pagi hari dan sore hari
(Handayani & Nofyan 2015) dan pH yang ideal dimana ikan patin akan mengalami
pertumbuhan yang optimum berkisar antara 6,5-9,0 (Adriyanto dkk. 2012). Menurut
Legendre et al., (2000) konsentrasi
oksigen terlarut di atas 3 mg.L-1 masih
termasuk dalam batas toleransi ikan patin. Ogbonna and Amajuoyo (2010),
menyatakan bahwa kandungan ammonia sebesar 0,6 mg/liter sudah berbahaya bagi
organisme perairan.
Penyebaran
ikan patin meliputi berbagai negara diantaranya adalah Thailand, Pakistan,
Myanmar, Bangladesh, Malaya-peninsula, Laos, India, Vietnam, dan Indonesia
(Chondar, 1999). Di Indonesia, patin terdapat di sungai dan danau-danau di
pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa (Djarijah, 2001). Umumnya, ikan ini
ditemukan di lokasi-lokasi tertentu di bagian sungai, seperti lubuk (lembah
sungai) yang dalam.
❤ Kebiasaan Makan
Ikan patin merupakan ikan omnivora
yang cenderung karnivora. Ikan patin pada fase larva yang dipelihara di kolam
pemeliharaan bersifat omnivora, yaitu memakan segala macam pakan baik
jasad-jasad hewani maupun nabati sedangkan ikan patin apabila di perairan bebas
dan alam cenderung bersifat karnivora (Cholik et al., 2005)
Ikan
patin sangat tanggap terhadap pakan buatan hal ini dibuktikan pada penelitian
Arifin (1993) bahwa ikan patin yang dipelihara di jaring apung responsif
apabila diberikan pakan. Pada proses
budidaya dalam usia enam bulan ikan patin bisa mencapai panjang 35-40 cm.
❤ Kebutuhan Nutrisi Ikan Patin
Ikan patin siam (Pangasius hypophthalmus) adalah spesies ikan air tawar dari famili Pangasidae dan merupakan salah satu spesies ikan yang memiliki nilai ekonomis untuk dibudidayakan. Tercatat pada tahun 2011, produksi ikan patin di Indonesia mencapai 229.267 ton dengan kontribusi 16,11% dari produksi patin dunia (FAO, 2013). Ikan patin siam memiliki keunggulan tidak memiliki banyak duri, fekunditas dan sintasannya tinggi, dapat diproduksi secara massal dan memiliki peluang pengembangan skala industri. Dengan keunggulan tersebut ikan ini menjadi salah satu komoditas perikanan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, baik dalam segmen usaha pembenihan maupun usaha pembesarannya (Tahapari dkk, 2008). Peningkatan produksi ikan patin melalui kegiatan budidaya diperlukan input produksi yang juga meningkat, salah satunya adalah pakan.
Kebutuhan
nutrisi ikan sangat penting untuk proses tumbuh kembang ikan itu sendiri,
nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan diantaranya protein, karbohidrat, dan lemak
(Putri dkk., 2012). Protein adalah kompleks yang terdiri dari asam amino
esensial dan non esensial (Andriyani dkk., 2014) yang berfungsi untuk
pertumbuhan ikan. Protein dapat digunakan untuk pertumbuhan jika kandungan
lemak dan karbohidrat seimbang, karena jika tidak maka protein tersebut lebih
banyak digunakan untuk energi dibandingkan untuk pertumbuhan (Poernomo dkk.
2015). Catfish membutuhkan kandungan
protein dalam pakan sekitar 25 – 50% tergantung ukuran ikan, suhu perairan,
jumlah energi non protein pada pakan, kualitas protein dan manajemen pakan
(Robinson et al., 2001), sedangkan
menurut NRC (2011) kebutuhan protein untuk Channel
catfish yaitu 28-40%. Berdasarkan SNI (2000), kebutuhan protein pada ikan
patin minimal 28%. Karbohidrat berfungsi
untuk memenuhi kebutuhan energi dan persediaan makanan dalam tubuh (Suarez et al., 2002). Sedangkan lemak berfungsi
sebagai pemasok energi bagi tubuh. Sebagian besar ikan air tawar membutuhkan
lemak 4% - 8%. (Afrianto dan Liviawaty, 2005). Serat kasar yang tinggi akan
mengakibatkan semakin sulitnya ikan dalam mencerna pakan (Bakara, dkk. 2012).
Pada umumnya, Ikan karnivora dapat mentoleransi serat kasar pada pakan maksimal
4% sedangkan ikan herbivora maksimal 8% (Priskila, 2010).
Pakan
dengan kadar protein 30% dan lemak 12% untuk benih ikan patin ukuran 3g dapat
menghasilkan laju pertumbuhan sebesar 2,06% /hari dan menghasilkan ikan dengan
kandungan protein tubuh 12,03%, lemak 5,22% dan air 75,63% (Phumee et al., 2009). Pakan dengan kandungan protein
45,3% dan lemak 9% untuk ikan patin ukuran 5g dapat menghasilkan laju
pertumbuhan 4,19% /hari dan menghasilkan ikan dengan kandungan protein tubuh
14,6%, lemak 6,3%, dan air 75,9% (Liu et al., 2011). Pakan dengan kadar protein
36,1% dan lemak 5,8% yang diberikan pada ikan patin ukuran 7,69g menghasilkan
laju pertumbuhan 4,0% /hari (Hung et al.,
2004).
❤ Daftar Pustaka
Afrianto, E.,
dan E. Liviawaty. 2005. Pakan Ikan. Kanisius : Yogyakarta. Hal 9-77.
Andriyani, H.,
E. Widyatusti dan D. S. Wisyartini. 2014. Kelimpahan Chlorophyta Pada Media
Budidaya Ikan Nila yang Diberi Pakan Fermentasi Dengan Penambahan Tepung Kulit
Ubi Kayu dan Probiotik. Scripta Biologica, 1 (1): 49-54.
Bakara,O., L.
Santoso. dan D. Heptarina. 2012. Enzim Manase dan Fermentasi Jamur untuk
Meningkatkan Kandungan Nutrisi Bungkil Inti Sawit pada Pakan Ikan Nila Best (Oreochromis niloticus). Jurnal Ilmu
Perikanan dan Sumberdaya Perairan. Hal 1.
BSN., 2000. SNI
01-6483.2-2000 Benih ikan patin siam (Pangasius
hypopthalmus) kelas benih sebar. Badan Standarisasi Nasional.
Cholik,F., A. G.
Jagatraya., R. P. Poernomo dan A. Jauzi. 2005. Akuakultur : Tumpuan Harapan
Masa Depan Bangsa. Masyarakat Perikanan Nusantara Kerjasama dengan Taman
Akuarium Air Tawar. Jakarta. 415 hal.
Chondar SL.1999.
Biology of Finfish and Shellfish. SCSC Publishers, India.
Djarijah, A. S,
2001. Pembenihan Patin. Kanisius. Yogyakarta.
Food and
Agriculture Organization (FAO). 2013. Milk
and Dairy Products in Human Nutrition. Rome: Food and Agriculture
Organization of The United Nations. 45-70.
Ghufron, K.K.
2005. Budidaya Ikan Patin. Yayasan Pustaka Nusatama. Yogyakarta.
Handayani I, E Nofyan. 2015. Optimasi tingkat
pemberian pakan bautan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan patin
jambal (Pangasius djambal). Jurnal
Akuakultur Rawa Indonesia, 2(2): 175-187.
Hung LT, Suhenda
N, Slembrouck J, Lazard J, Moreau Y. 2004. Comparison of dietary protein and
energy utilization in three Asian catfish Pangasius
bocourty, P. hypophthalmus and P. djambal. Aquaculture Nutrition 10:
317–326.
Kordi, M. G. H.
2005. Budidaya Ikan Patin : Biologi, Pembenihan dan Pembesaran. Yayasan Pustaka
Nusatama, Yogyakarta.
Liu . X. Y, Wang
Y, J.I WX. 2011. Growth, feed utilization and body consumption of Asian catfish
Pangasius hypopthalamus feed at
different dietary protein and lipid levels. Aquaculture Nutrition 11: 578–584.
National
Research Council [NRC]. 2011. Nutrient Requirements of Fish National Academy
Press, Washington, DC: NRC.
Ogbonna, J. and
A. Chinomso. 2010. Determination of the concentration of ammonia that could
have lethal effect on fishpond. Journal of Engineering and Applied Sciences:
5(2) :1-5.
Phumee P, Hashim
R, Aliyu-Paiko M, ShuChien AC. 2009. Effects of dietary protein and lipid
content on growth performance and biological indices of iridescent shark Pangasius hypophthalmus, Sauvage 1878
fry. Aquaculture Research 40: 456–463.
Poernomo, N., N.
B. P. Utomo., dan Z. I. Azwar. 2015. Pertumbuhan dan Kualitas Daging Ikan Patin
Siam yang Diberi Kadar Protein Pakan Berbeda.Jurnal Akuakultur Indonesia 14(2),
104-111.
Priskila, F. 2007.
Pengaruh Penggunaan Kombucha terhadap Kandungan Protein Kasar dan Serat Kasar
pada Fermentasi Daun Talas (Colocosia
esculenta). Skripsi. Program Studi S1 Budidaya Perairan. Fakultas Kedokteran
Hewan. Universitas Airlangga. Surabaya. 55 hal.
Putri,D.R.,
Agustono., dan S. Subekti. 2012. Kandungan Bahan Kering, Serat Kasar, dan
Protein Kasar pada Daun Lamtoro (Leucema
glauca) yang Difermentasi dengan Probiotik Sebagai Bahan Pakan Ikan. Jurnal
Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 4 (2) : 161-167.
Robinson, E. H., Li, M. H.,and Manning, B. B. 2001.
Evaluation of corn gluten feed as a dietary ingredient for pond raised channel
catfish Ictalurus punctatus. J. World Aquacult. Soc., 32 (1):
68-71.
Saanin, 1984.
Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan Volume I dan II. Bina Rupa Aksara.
Jakarta.
Suarez, M.D., A
Sanz, J. Bazoco, & M.G. Gallego. 2002. Metabolic Effects of Changes in the
Dietary Protein: Carbohydrate Ratio in Eel (Angilla
anguilla) and Trout (Oncorhynchus
mykiss). Aquaculture International. 10(3): 143–156.
Tahapari, E. dan
Arianto, D. dan Gunadi, B. 2008. Optimasi pemberian pakan buatan pada
pendederan ikan patin (Pangasius hypophthalmus). Jurnal perikanan.